Pulang kampung setelah lima tahun di rantau menuntut ilmu, memberi warna tersendiri dalam hati. Dengan mengantongi ijazah sarjana, aku melangkah tegap menuju bus yang akan membawaku ke Doro, sebuah kota kecamatan kecil 20 km di sebelah selatan Pekalongan.
Bus Binatur yang kutumpangi berjalan lambat keluar terminal. Tidak hanya sekali dua bus berhenti untuk menaik-turunkan penumpang. Bahkan beberapa kali bus malah berjalan mundur, masuk ke jalan desa, menjemput penumpang yang hampir terlewat.
Sampai di perempatan Karangdadap langit gelap. Sesaat kemudian turun hujan. Kuedarkan pandang ke luar jendela. Lewat kaca bus yang buram, kulihat butiran mutiara itu berlomba turun menjejak ke bumi. Banyak rumah baru berdiri di sepanjang pundak jalan yang tidak seberapa luas.
Sejam kemudian, tepat pukul 12.00 siang, bus sampai di depan Pasar Doro. Di kota kecil ini tak ada terminal bus, yang ada hanyalah terminal colt angkutan pedesaan. Itu pun tak seluruh colt masuk ke terminal. Banyak di antaranya yang nge-tem di depan pasar sebelah barat, berbaur jadi satu dengan bus yang akan datang.
“Masih seperti dulu,” gumamku membatin, ketika melihat sebuah colt jurusan Karanganyar berangkat. Ya, masih seperti dulu. Colt berangkat dengan penumpang yang berjejal sesak. Dari belakang yang terlihat jajaran orang bergelantungan rapat membentuk teralis menutupi bagian belakang mobil. Dan kalau belum mendapat penumpang yang rapat seperti itu, colt memang belum mau berangkat. Padahal itu sungguh membahayakan keselamatan penumpang.
Aku menarik napas untuk melonggarkan dadaku yang sesak. Dengan jilbabku yang bersih ini, aku pun akan berimpit seperti mereka. Berdesak dengan orang, barang belanjaan, dan ayam. Sudah tercium olehku keringat bercampur kubis busuk, tai ayam, dan aroma parfum yang tajam menusuk. Seperti itulah kalau perjalanan kita lekas sampai, karena jumlah angkutan di sini sangat terbatas.
Colt jurusan Lemahabang yang kutumpangi hampir penuh. Beruntung aku mendapat tempat duduk di depan, di ruang kemudi. Meski sesak juga, tapi tak separah seperti duduk di belakang. Lumayanlah. Tapi harap diingat, mendapat tempat duduk di ruang sopir, harus berani membayar lebih, karena lebih nyaman, maka ruang sopir ini banyak diperebutkan.
Calo sudah memintai ongkos para penumpang. Berarti colt sudah penuh dan siap berangkat. Aku bernapas lega.
Pak sopir masuk ruang kemudi, lalu menghidupkan mesin. Saat itu melintas sebuah bayangan yang sudah sangat kukenal, di depan colt. Aku masih mengingatnya dengan baik, itu adalah bayangan Silva, taman sekampung, teman masa kecil, teman sepermainanku dulu. Kalau ia mau pulang, kenapa tidak naik colt ini? Dorongan rasa kangen pada sahabat telah mengalahkan kepentinganku untuk cepat-cepat sampai di rumah.
“Sebentar, Pak Sopir,” pintaku pada sopir yang sudah memasukan perseneling ke gigi satu. Lalu begitu saja aku turun dari mobil, mengejar Silva.
Terdengar teriakan sopir di belakang, “Cepat, Dik!”
Sekilas aku menoleh seraya melambaikan tangan menyuruhnya pergi. Sopir maklum, colt itu pun berangkat.
Aku berhasil mengejar Silva. Kujajari langkahnya.
“Mau kemana?” tanyaku.
Silva menoleh, tersenyum. Wajah dan bibirnya tampak pucat, tapi kakinya melangkah ke arah timur.
“Mestinya kamu bersama saya naik colt yang tadi. Kamu sudah tahu kan, selepas colt tadi belum tentu ada colt berikutnya yang bisa membawa kita pulang? Sudah siang begini tak ada lagi orang berpergian. Anak sekolah dan ibu-ibu yang belanja sudah pada pulang. Kita pertaruhkan pada nasib baik untuk bisa pulang hari ini.”
Silva tak berkomentar. Kucoba menggandeng tangannya. Dingin. “Kamu sakit? Mau periksa? Okelah, aku menemanimu.”
Melewati sebuah jembatan kecil, Silva belok ke kiri.
“Lho, kalau mau periksa ke tempat dr. Lestari, beloknya ke kanan, dong?!” protesku. Silva tak menanggapi protesku. Ia terus saja melangkah.
“Baiklah, kuikuti kamu,” kataku, menyerah. “Seandainya nanti tidak mendapat colt pulang, toh ada kamu. Kita bisa pulang jalan kaki bersama.
Kami lewat di depan KUA. Ke utara sedikit, ada masjid di sisi barat jalan, menghadap ke timur. Silva membelokkan langkahnya ke sana.
“Oh, kamu mengajakku salat dulu? Baiklah. Sekarang memang sudah hampir jam satu,” kataku, setelah melirik arloji di pergelangan tanganku.
Aku mendahului Silva melepas sepatu, terus ke kamar kecil. Setelah itu mengambil wudhu dan salat Zuhur lebih dahulu, karena Silva tak tampak bayangannya. Kupikir ia sedang berada di kamar kecil.
Kemana sih, dia? Diikuti kok malah menghilang? gerutuku sendirian, sambil mengenakan sepatu bersiap meninggalkan masjid.
Aku kembali ke depan pasar mencari angkutan. Suatu kebetulan, ada serombongan orang yang hendak berziarah ke makam Syeh Siti Jenar di Lemahabang. Mereka mendapatkan colt dan aku mengikuti saja. Tampaknya rombongan itu membayar lebih, sehingga tak usah menunggu penumpang berdesak. Alhamdulillah.
Mobil yang kami tumpangi bergerak ke arah barat setengah kilo, lalu berbelok ke selatan. Dan mulailah perjalanan yang penuh risiko. Karena colt mesti melewati jalan berbatu tidak rata, dengan medan yang terus menanjak. Badan colt bergerak seperti layaknya tubuh mentok. Merangkak tertatih, megal-megol, oleng ke kiri dan ke kanan, kepalanya mengangguk-angguk.
Setelah lepas empat puluh lima menit, colt yang sudah bergerak pelan, terasa semakin memperlambat lajunya. Kami saling bertatapan. Ada apa? Serentak kami arahkan pandangan ke depan. Ada sekerumunan orang memenuhi jalan di depan. Colt berhenti. Kami turun untuk mencari tahu.
Ternyata ada colt jatuh ke jurang! Sebagian penumpangnya tewas, sebagian yang lain luka-luka. Mereka sedang dievakuasi. Dan itu adalah colt yang hendak kutumpangi tadi, tapi tidak jadi!
Aku tertunduk lemas. Tak henti-hentinya kusebut kebesaran nama-Nya. Pandanganku yang kabur oleh airmata, menangkap tubuh-tubuh yang berlumpur dan berlumur darah terkulai. Pecahan kaca yang berserakan. Mobil yang ringsek. Wajah-wajah yang basah oleh airmata. Telingaku menangkap raungan tangis tak beraturan dari mereka yang masih bisa menagis. Allah Mahabesar.
“Dik, naik lagi. Kita teruskan perjalanan,” kata sebuah suara.
Kuusap mataku dengan punggung tangan. Tanpa suara kuikuti laki-laki yang berkata tadi. Lalu kami masuk kembali ke colt untuk meneruskan perjalanan.
Begitu sampai di rumah, setengah berlari aku menuju ke rumah Silva. Dia sendiri yang membukakan pintu. Serentak melihat bayangannya, langsung kutubruk dan kupeluk ia. Tangisku pun tumpah di pundaknya.
Silva balas memeluk.
“Tenanglah…,” bisiknya lembut dekat telingaku. Dipapahnya tubuhku menuju ke kamarnya. Setelah meminum air putih pemberian Silva, aku sedikit lebih tenang. Lalu kuceritakan semua kepadanya. Tentang pertemuanku dengannya di depan pasar. Tentang salatku di masjid. Juga tentang colt yang tak jadi kutumpangi dan ternyata mendapat kecelakaan…
“Kuminta jawablah pertanyaanku dengan jujur. Di mana saja kamu seharian ini?”
“Seharian ini aku hanya di rumah, tidak pergi ke mana-mana. Sungguh! Kalau tak percaya, tanya Ibu,”kata Silva, serius. “Sejak pagi sampai menjelang Zuhur, aku di sawah bersama Ibu, matun padi. Pulang dari sawah aku mampir ke pancuran, bersih-bersih sekalian ambil air wudhu. Setelah salat dan makan, istirahat sambil membaca-baca. Lalu kamu datang,” jalas Silva runut.
“Aku percaya. Lantas, siapa gadis mirip kamu yang kutemukan di depan pasar?”
Kami saling berdiam diri, digayuti oleh pikiran masing-masing.
Dan aku percaya, Allah memang sengaja menyelamatkanku dengan cara-Nya sendiri. Terima kasih, ya Allah, atas pertolongan-Mu. Tak henti-hentinya kusebut nama-Nya.
http://fadil.blogsome.com/2009/09/29/sahabat/
Selasa, 15 Februari 2011
Sahabat
 02.17
02.17
 Anzilina Nisa'
Anzilina Nisa'
 RSS Feed
RSS Feed Twitter
Twitter
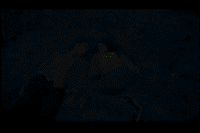



0 komentar:
Posting Komentar